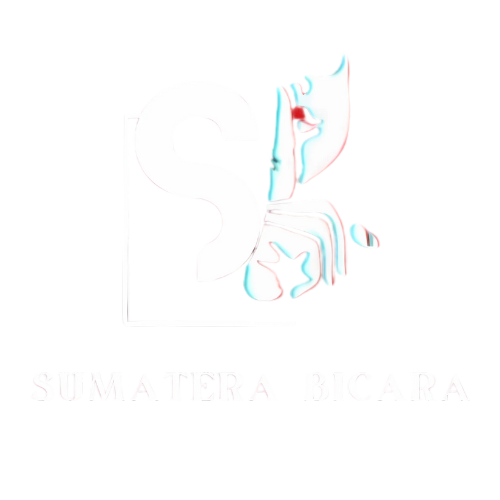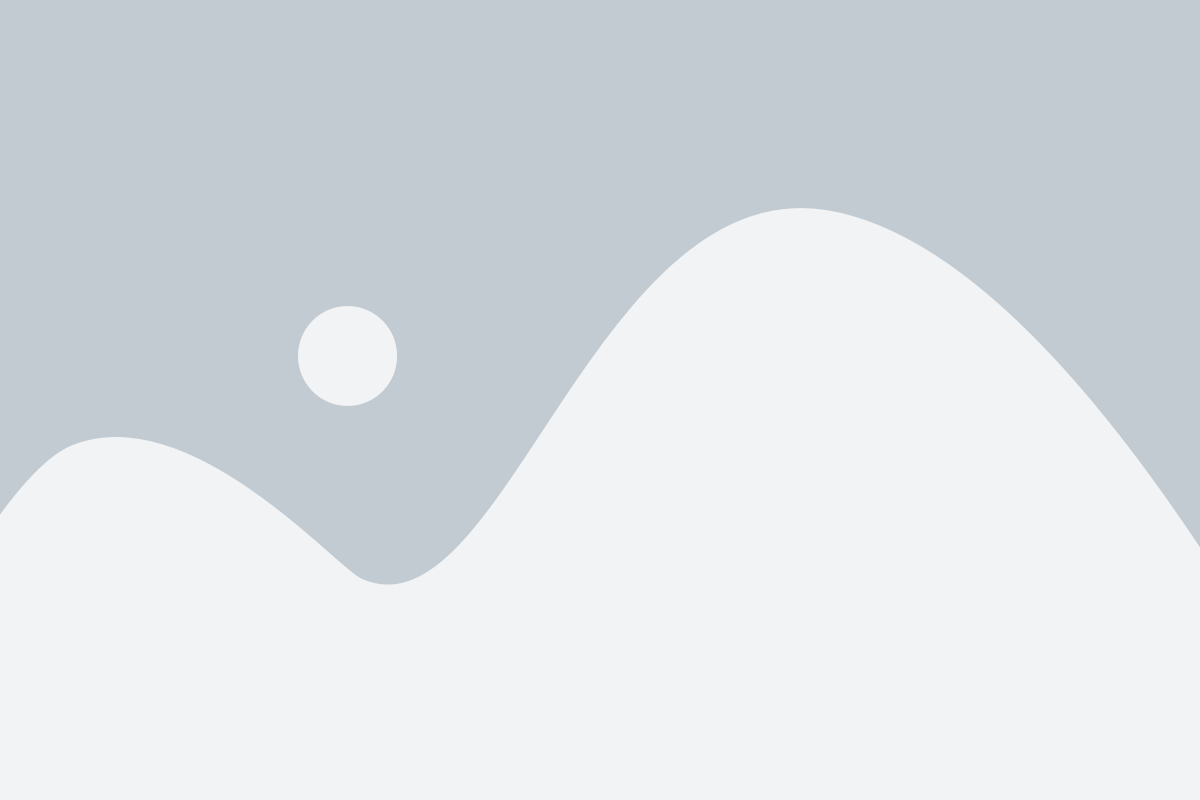MURATARA – Fajar baru saja menyibak kabut tipis di atas Sungai Rawas, ketika suara mesin gergaji memecah keheningan pagi. Getaran dari batang kayu yang tumbang menggema hingga ke dasar tanah. Di sinilah, di jantung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang membentang megah dan tenang, kehidupan hutan perlahan-lahan tereduksi menjadi tumpukan papan.
Di desa-desa sekitar perbatasan Muratara, Sumatera Selatan, perambahan hutan bukan lagi cerita tersembunyi. Ia adalah denyut kehidupan, paradoks yang diam-diam diterima. “Kami menyebutnya bekayu,” ujar Masrip, warga Kecamatan Rupit. “Itu pekerjaan turun-temurun. Mau makan apa lagi kalau bukan dari situ?”
TNKS, salah satu paru-paru dunia yang diakui UNESCO, seolah tak lagi punya suara. Setiap hari, puluhan perahu kayu melaju di arus sungai membawa batang-batang besar yang ditebang dari dalam kawasan hutan lindung. Kayu-kayu itu mengapung, seperti mayat yang dihanyutkan dari rimba sekarat.
Bagi Sutar (nama disamarkan), sungai adalah jalan utama. “Kalau lewat darat bisa dua hari, tapi lewat sungai cuma sehari dengan perahu ketek, 30 liter solar cukup,” katanya. Ia menyebut dua jenis perjalanan: trip dekat—mengambil kayu dari hutan rakyat, dan trip jauh menembus dalamnya TNKS di tapal batas Sumsel dan Bengkulu.
Anak sungai Rawas dan Sungai Rupit seperti Sungai Minak, Sungai Tiku, hingga Sungai Maling, menjadi jalur pengangkutan utama. Di malam hari, ketika bulan tinggi, suara perahu-perahu bermesin kecil menggantikan dengung jangkrik. Mereka membawa hasil tebang dari titik-titik perambahan Desa Ulu Sebelas, Tik Serong, hingga perbatasan Karang Jaya.
Kayu yang diangkut itu bernilai tinggi—antara Rp1,4 juta hingga Rp3,4 juta per meter kubik, tergantung jenisnya. Satu truk bisa membawa 8 hingga 10 kubik. Tak heran, dalam sehari diperkirakan 30 truk melintas membawa hasil rambahan. Di sepanjang jalan, desa-desa seperti Suka Menang, Pulau Kidak, Rawas Ulu dan wilayah Rupit menjadi titik pengepulan.
Di atas kertas, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) memiliki luas hutan sekitar 604.020,92 hektare. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung dan suaka alam yang termasuk dalam TNKS. Namun, aktivitas perambahan hutan dan illegal logging telah menyebabkan kerusakan signifikan.
Di wilayah pengelolaan TNKS Wilayah V Lubuklinggau, yang mencakup Muratara, tercatat sekitar 3.158 hektare hutan telah mengalami kerusakan akibat perambahan, termasuk di wilayah inti taman nasional.
Namun, pemerintah juga tahu: ini bukan hanya soal hukum. Ini tentang perut rakyat. Di desa-desa sekitar TNKS, tidak ada industri, tidak ada lapangan kerja tetap. Bekayu bukan sekadar pilihan, melainkan satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan.
TNKS adalah warisan untuk generasi masa depan. Kami akan lakukan moratorium pemanfaatan hasil kayu dari dua kecamatan yang berbatasan langsung.
Hutan tak pernah membalas ketika ditebang. Ia hanya menyimpan luka dalam diam, hingga luka itu menjelma jadi bencana. Longsor menutup jalan desa. Banjir bandang merusak sawah. Air kering di musim kemarau. Itulah balasan yang tak tertulis dari sebuah ekosistem yang tak lagi seimbang.
TNKS bukan sekadar hamparan pepohonan. Ia adalah rumah bagi harimau Sumatra, gajah liar, ribuan spesies burung, dan jutaan pohon yang menyimpan oksigen dunia. Saat satu pohon tumbang, dunia kehilangan sesuatu meski kecil, tapi berharga.
Tak hanya aksi ilegal logging yang membabat hutan lindung di Muratara, namun banyaknya perusahaan perkebunan sawit yang bercokol juga ikut membasmi pohon pohon rimba di wilayah ini.
“Kami Dipaksa Jadi Warga Kota”: Ratapan Sunyi dari Warga Rimba Muratara
Jafarin duduk bersila di atas tikar pandan. Rambutnya mulai memutih, namun sorot matanya masih tajam seperti harimau tua yang mengawasi batas wilayahnya. Dia adalah Kepala Suku Anak Dalam, penjaga warisan rimba yang semakin hari terasa asing baginya.
“Dulu, kami tidak kenal tembok,” katanya pelan, menatap ke arah barisan pohon yang kini kian langka. “Hutan itu rumah kami. Di sanalah kami berburu, meramu, dan hidup damai. Tapi sekarang, semua itu tinggal kenangan.” Katanya.
Jafarin tak sedang menggambarkan nostalgia, melainkan kenyataan pahit yang harus mereka telan. Hutan-hutan lebat tempat generasi mereka hidup secara turun-temurun, perlahan diratakan. Diganti oleh hamparan kelapa sawit milik perusahaan. Sebagian warga SAD, termasuk keluarganya, dipaksa pindah dari hutan yang dulu mereka jaga.
“Kami diajari hidup menetap, makan dari pasar, bekerja di ladang sawit milik orang lain. Padahal, hutan tempat kami bergantung itu, hilang berubah jadi kebon sawit.” cerita Jafarin
Bagi masyarakat Suku Anak Dalam, kehilangan hutan bukan sekadar kehilangan tempat tinggal. Itu adalah identitas. Mereka yang dulu dihormati sebagai penjaga alam, kini dicurigai sebagai pencuri buah sawit.
“Hutan itu bukan hanya tempat bagi kami. Tapi guru, pelindung, bahkan teman,” kata Jafarin. “Ketika hutan dibabat, kami tidak hanya kehilangan tanah. Kami kehilangan jati diri.” Keluhnya
Kini, anak-anak SAD tumbuh tanpa mengenal lagi pohon sialang, tanpa tahu bagaimana mencari jejak rusa, atau bagaimana mendengar pesan angin yang berembus dari celah dedaunan. Dunia yang mereka warisi telah berubah menjadi barisan kebun monokultur, dijaga oleh pagar dan aturan yang tak mereka pahami.
Jafarin tahu mereka tak bisa melawan perubahan. Tapi dia berharap masih ada ruang untuk suara mereka didengar. “Kami tidak menolak kemajuan. Kami hanya ingin dihormati. Jangan ambil semua dari kami. Sisakan hutan, agar anak cucu kami tahu, bahwa dulu mereka pernah punya rumah yang bernama rimba.” Pintanya. (SM)