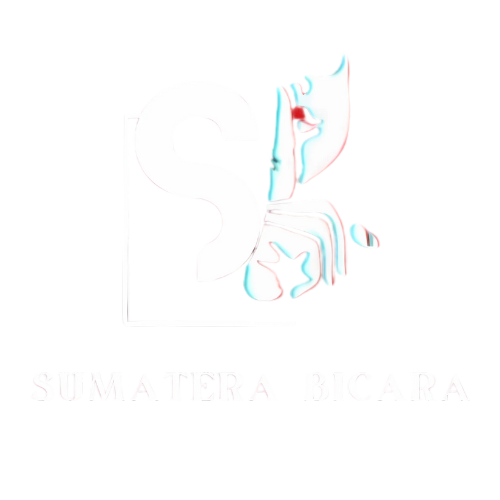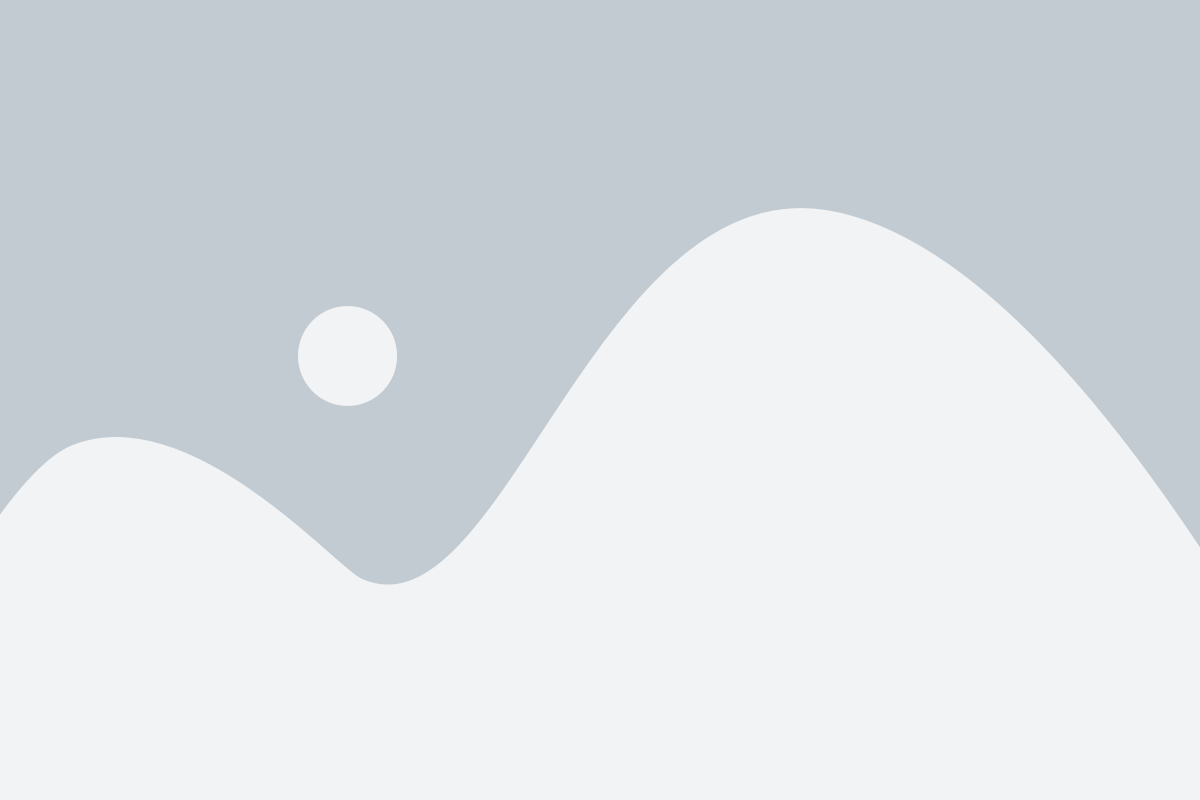Sumatra – Di balik lebatnya hutan hujan tropis Sumatra, suara alam masih terdengar lirih meski terancam lenyap. Di sana, di antara pucuk-pucuk pohon yang menjulang, hidup makhluk yang menyendiri, tenang namun penuh daya – Pongo abelii, orangutan Sumatera. Mamalia besar yang kini hidup dalam bayang-bayang kepunahan.
Di pagi yang lembap, sinar mentari menembus celah dedaunan, memantulkan kilau lembut pada bulu jingga seekor induk orangutan yang mengayun perlahan di antara ranting pohon. Di pelukannya, seekor bayi mungil mencengkeram erat, menggantungkan hidup sepenuhnya pada sang ibu. Inilah gambaran kehidupan primata yang hanya ditemukan di pulau Sumatra – dan sebagian kecil populasi di hutan Leuser, Aceh, yang menjadi benteng terakhir mereka.
Namun, kenyataan tak seindah bentang alamnya. Setiap tahun, habitat mereka menyempit akibat ekspansi perkebunan sawit, pembalakan liar, dan pembangunan yang tak ramah lingkungan. Menurut data Forum Konservasi Orangutan Indonesia (FORINA), populasi orangutan Sumatera kini diperkirakan tinggal kurang dari 14.000 ekor di alam liar. Jumlah itu terus menurun, bersaing dengan waktu dan kerakusan manusia.
Muhammad Reza, seorang pegiat konservasi di kawasan Ekosistem Leuser, mengenang perjumpaannya dengan orangutan liar sebagai pengalaman yang mengubah hidup.
“Waktu itu saya melihat seekor jantan besar, matanya menatap saya tajam tapi damai. Seolah dia tahu dia hanya punya waktu sedikit lagi di dunia ini,” kata Reza dengan mata berkaca.
Ia dan timnya rutin berpatroli di hutan, menyusuri jalur-jalur sempit untuk memantau populasi dan memastikan tak ada perburuan. Tantangannya tidak ringan. Selain medan yang sulit, mereka juga berhadapan dengan para pelaku ilegal logging yang kerap bersenjata.
Upaya konservasi pun terus dilakukan oleh berbagai pihak. Di Sumatera Utara, Pusat Rehabilitasi Orangutan di Batu Mbelin dan Sumatra Orangutan Conservation Programme (SOCP) menjadi harapan baru. Mereka menyelamatkan orangutan dari perdagangan ilegal dan pelepasan kembali ke hutan jika memungkinkan.
Namun, menurut Eva Rahmi, peneliti primata di Universitas Syiah Kuala, konservasi bukan hanya tentang menyelamatkan individu. Ini tentang menjaga ekosistem.
“Orangutan adalah penjaga hutan. Mereka menyebarkan biji, menjaga keseimbangan ekologi. Jika mereka hilang, hutan pun bisa runtuh pelan-pelan,” ujarnya.
Kini, suara jerit gergaji mesin dan derap ekskavator masih kerap terdengar di perbatasan hutan. Hutan yang dulunya menjadi rumah ribuan spesies kini tinggal fragmen-fragmen kecil yang tersebar dan terisolasi.
Masyarakat lokal sebenarnya punya peran besar. Di beberapa desa di perbatasan hutan, mulai tumbuh kesadaran untuk hidup berdampingan. Program ekowisata dan pelatihan pertanian ramah lingkungan mulai diperkenalkan.
Di tengah semua tantangan, harapan belum padam. Selama masih ada mereka yang percaya bahwa makhluk lembut itu layak dipertahankan, orangutan Sumatera akan terus bergelayut di antara dahan-dahan terakhirnya.
Ade, Harapan Baru dari Hutan yang Terluka
Di suatu sudut sunyi di Lembaga Konservasi (LK) Kasang Kulim, Riau, kehidupan baru hadir dengan tenang. Seekor bayi orangutan mungil, berjenis kelamin jantan, lahir pada Jumat, 2 Mei 2025. Ia belum bisa bicara, tapi kehadirannya telah menyampaikan pesan besar: harapan.
Bayi itu diberi nama Ade, sebuah nama sederhana namun sarat makna, langsung diberikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang mengunjungi lembaga tersebut dua pekan setelah kelahiran sang bayi. Ade adalah anak dari pasangan orangutan titipan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau – Susi dan Yongki, dua individu dari spesies yang kini kian terancam di alam liar.
“Kondisi bayi orangutan dalam keadaan sehat dan mulai aktif menyusu dari induknya. Ini adalah kabar menggembirakan bagi konservasi satwa kita,” ujar Raja Juli, Senin (19/5), dalam pernyataan resminya.
Kelahiran Ade bukan hanya tentang bertambahnya koleksi satwa di LK Kasang Kulim. Ia adalah simbol kelanjutan dari perjuangan melawan waktu – perjuangan menjaga spesies yang masuk dalam daftar endangered menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List.
Supartono, Kepala Balai Besar KSDA Riau, menyadari betul pentingnya kelahiran ini. Ia langsung memberikan arahan kepada para perawat satwa dan pengelola lembaga konservasi.
“Pakan untuk induknya harus cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Nutrisi yang tepat adalah kunci bagi kesehatan Susi dan tumbuh kembang Ade,” tegasnya.
Orangutan tidak seperti hewan lain yang bisa dengan mudah berkembang biak. Masa kehamilan mereka panjang, hingga sembilan bulan, dan biasanya hanya melahirkan satu anak dalam beberapa tahun. Hubungan ibu dan anak juga sangat erat, di mana bayi bergantung pada induknya hingga usia 6–8 tahun.
Karena itulah, kelahiran di lembaga konservasi seperti ini bukan sekadar pencapaian biologis. Menurut Satyawan Pudyatmoko, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), ini merupakan bukti keberhasilan sistem pengelolaan konservasi yang terkontrol dan berstandar tinggi.
“Setiap kelahiran satwa liar di lembaga konservasi adalah indikator keberhasilan pengelolaan dan perawatan. Ini menunjukkan bahwa prinsip etika dan kesejahteraan satwa dijalankan dengan baik,” ungkap Satyawan.
Namun, di balik kabar gembira ini, dunia luar masih menyimpan ancaman bagi Ade dan kaumnya. Pembukaan lahan, pembalakan liar, dan perdagangan ilegal masih menjadi momok bagi kelangsungan hidup orangutan, khususnya di Pulau Sumatra dan Kalimantan.
Di ruang perawatan LK Kasang Kulim, Ade masih meringkuk di dada Susi. Matanya sesekali terbuka, memandang dunia yang baru dikenalnya. Ia belum tahu tentang bahaya yang menanti di luar sana, tentang pohon-pohon yang terus tumbang, atau sesamanya yang dijadikan peliharaan ilegal.
Tapi untuk saat ini, Ade aman. Dan mungkin, hanya mungkin, ia adalah awal dari lebih banyak kehidupan baru yang kelak akan kembali menghuni hutan-hutan Indonesia dengan bebas.(SM)