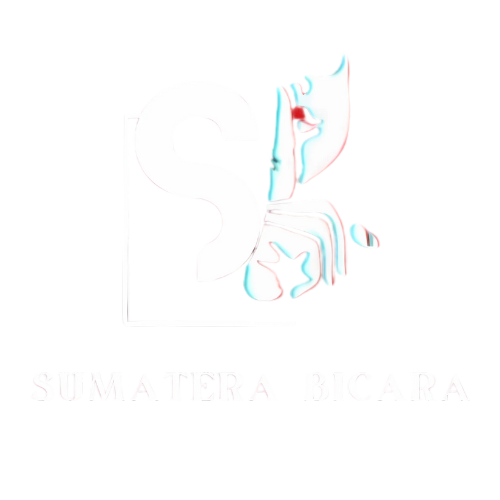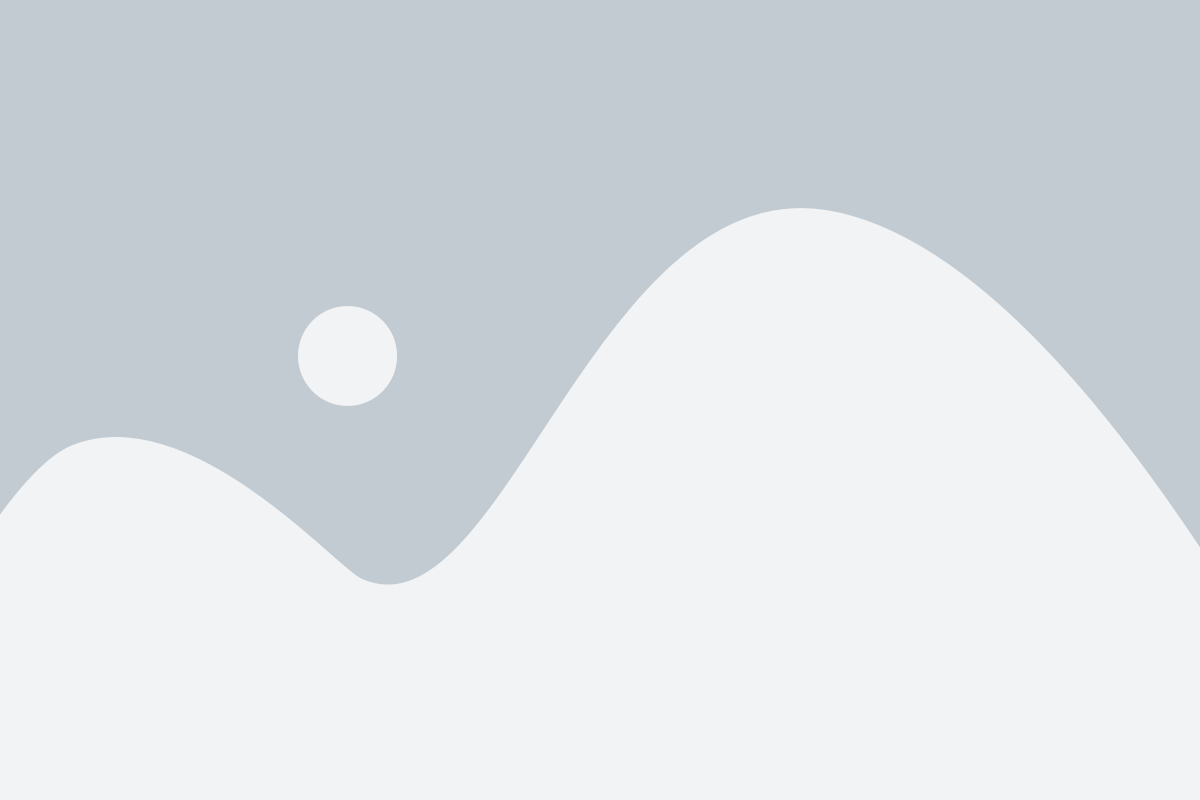SUMATERA— kabut tipis masih menyelimuti aliran Sungai Rupit yang membelah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan. Dari kejauhan, gemericik air sungai terdengar tenang. Namun di balik ketenangan itu, sebuah aktivitas mencurigakan tampak jelas di tepian sungai yang mengering sebagian.
Beberapa batang kayu besar tergeletak rapi di tepi sungai gersang. Sejumlah perahu ketek bersandar diam, sebagian di antaranya tampak telah dimuati potongan-potongan kayu panjang yang terlihat segar tanda glondong kayu baru ditebang. Dua hingga tiga orang pria terlihat sibuk mengatur posisi batang-batang kayu itu di atas rakit kayu. Tak ada papan nama, tak ada pengawasan resmi. Semuanya dilakukan dengan tenang, nyaris tanpa suara.
Pemandangan itu menguatkan dugaan adanya aktivitas illegal logging yang masih berlangsung di wilayah hulu Sungai Rupit dan Sungai Rawas. Bantaran sungai yang menjadi lokasi bongkar muat terlihat tandus dan terbuka. Tanpa naungan pohon, tanahnya tampak sering dilewati kendaraan atau aktivitas berat.
Sumber warga menyebutkan, kawasan tersebut kerap digunakan sebagai titik pengumpulan kayu hasil tebangan dari wilayah pedalaman atau uluan sungai Rupit dan Sungai Rawas.
“Sudah lama di sini seperti itu. Kadang malam hari baru ada suara ketek datang bawa kayu dari atas,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kayu-kayu tersebut diduga berasal dari kawasan hutan di bagian barat Muratara, wilayah yang dikenal masih memiliki hutan lebat namun minim pengawasan.
Aktivitas pengangkutan hasil hutan melalui jalur sungai bukan hal baru di Muratara. Modusnya pun klasik. Penebangan di hutan pedalaman, pengangkutan lewat sungai menggunakan rakit atau perahu kecil, lalu dibawa ke titik kumpul di bantaran sungai.
Dari sana, kayu akan diangkut menggunakan truk ke luar daerah seperti pulau jawa, kadang tanpa dilengkapi dokumen sah, kadang juga dilengkapi surat yang dimanipulasi seperti SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan).
Padahal, sesuai UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, aktivitas tersebut bisa dikenai sanksi pidana jika dilakukan tanpa izin resmi.
Namun hingga kini, aparat berwenang tampak kesulitan menindak para pelaku. Jalur sungai yang panjang dan sulit dijangkau, ditambah minimnya personel pengawasan di lapangan, membuat praktik ini terus berlangsung.
Aktivitas pembalakan liar ini menyimpan risiko besar. Berkurangnya tutupan hutan di hulu Sungai Rupit dapat memicu bencana ekologis, seperti banjir saat musim hujan dan kekeringan ekstrem saat musim kemarau. Tak hanya itu, habitat satwa liar seperti trenggiling, rusa, bahkan harimau Sumatera, terancam hilang.
Menurut aktivis lingkungan lokal, pembiaran terhadap praktik ilegal ini bisa menjadi bumerang bagi masyarakat sendiri.
“Kalau hutan terus dirusak, Sungai bisa kehilangan sumber air bersih alaminya. Ini bukan cuma soal kayu, tapi soal masa depan,” ujar Fidaus, pegiat lingkungan Hijau Muratara.
Informasi dari warga dan pemerhati lingkungan setempat mengungkap bahwa para pelaku menggunakan jalur anak sungai di kawasan hulu di wilayah uluan Sungai Rupit dan Sungai Rawas sebagai jalur masuk ke dalam hutan lindung. Kawasan seperti Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) disebut sebagai salah satu sasaran utama.
“Mereka tebang di sana, bawa kayu lewat anak sungai, kayu kayu dibuat rakit ditarik pakai perahu ketemu, sampai ke sungai besar seperti Sungai Rupit dan Rawa. Dari situ baru diangkut keluar pakai truk malam hari,” ungkap warga yang tinggal tak jauh dari lokasi.
Di wilayah pedalaman, persepsi masyarakat terhadap hutan lindung menjadi salah satu pemicu utama pembalakan. Banyak warga yang menyebut kawasan seperti TNKS sebagai “Hutan Adam” istilah lokal untuk hutan yang dianggap tidak bertuan dan bisa ditebang siapa saja.
“Orang bilang itu hutan Adam, hutan dari zaman dulu yang nggak ada yang punya. Jadi ya siapa cepat dia dapat,” kata warga lain yang sudah terbiasa melihat rakit-rakit kayu lewat di sungai dekat rumahnya.
Kayu yang ditebang umumnya dijual dalam bentuk gelondongan. Satu kubik kayu dihitung dari empat batang gelondong ukuran standar. Harga pasaran kayu ini di tingkat pengumpul mencapai Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta per kubik angka yang cukup menggiurkan di tengah keterbatasan ekonomi pedalaman.
Jenis kayu yang diburu bervariasi, mulai dari meranti, damar, hingga kayu keras seperti tembesu dan medang. Aktivitas penebangan tidak dilakukan oleh individu, melainkan oleh kelompok-kelompok kecil warga, masing-masing beranggotakan antara 6 hingga 12 orang. Mereka membentuk unit operasi yang masuk ke hutan lindung, menebang secara manual, kemudian menyusun gelondongan menjadi rakit atau ditarik ke sungai menggunakan perahu.
Kelompok ini biasanya berasal dari desa-desa sekitar hutan, dan memiliki jaringan tersendiri untuk menjual hasil tebangan. Pembagian hasil dilakukan secara tunai, dengan sistem bagi rata atau sistem bagi alat jika ada yang menyuplai perahu atau mesin.
Ironisnya, aktivitas sebesar ini berlangsung nyaris tanpa hambatan. Minimnya patroli hutan, lemahnya pengawasan jalur sungai, serta tidak optimalnya penegakan hukum membuat praktik ini semakin dimanja dan terus berlangsung lama.
Di sisi lain, dampak lingkungan mulai terasa. Debit Sungai Rupit dan Rawas mulai tidak stabil. Di musim hujan, luapan banjir melanda desa-desa bantaran. Saat kemarau, sungai mengering dan sumber air bersih sulit ditemukan.(SM)