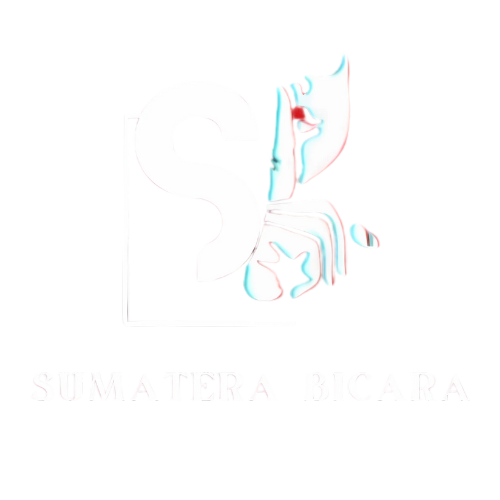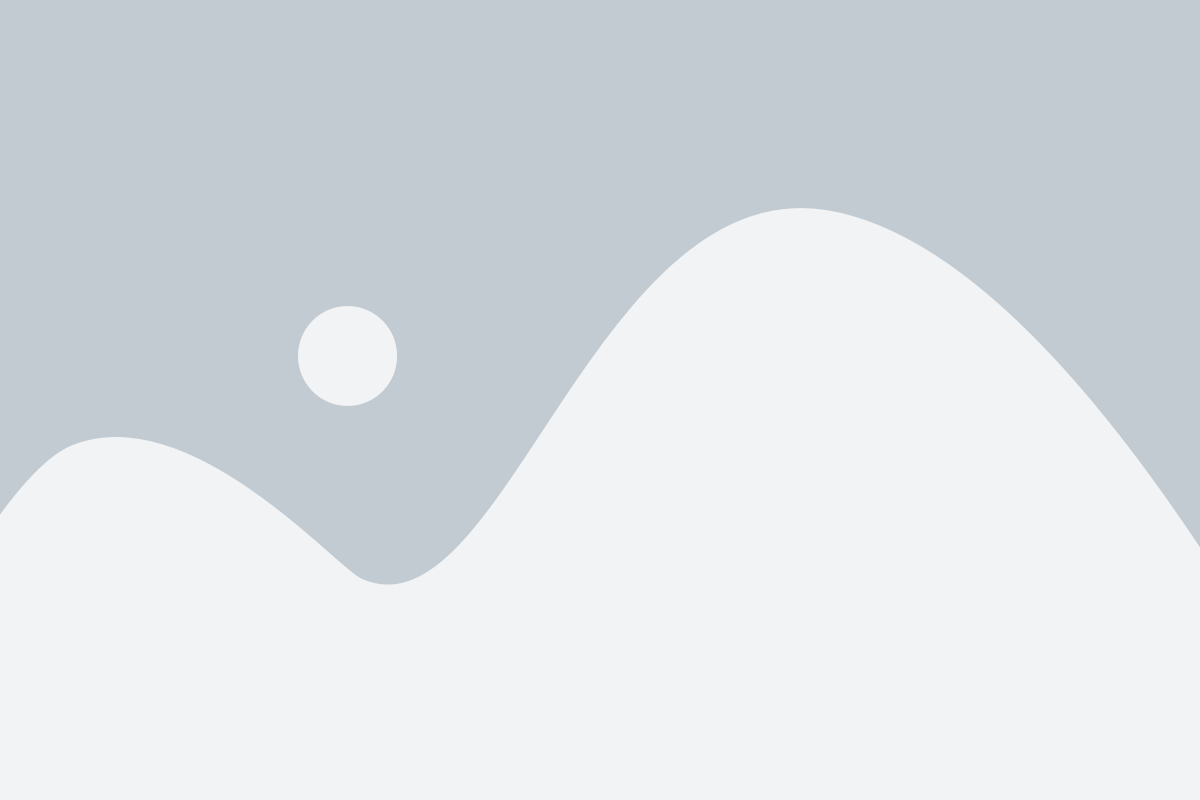Ketika Pulau-Pulau Jadi Pintu Masuk Emas Bagi Kartel Sabu Asia
Pulau Sumatera — Di tengah birunya lautan dan ketenangan pantai timur Sumatera, sebuah jalur gelap berdenyut kencang membawa racun paling mematikan dalam sejarah Indonesia: sabu-sabu. Seolah tak terjamah, jalur laut dari Cina ke Malaysia hingga pantai timur Sumatera kini dikenal sebagai “jalur neraka”—tempat awal narkotika masuk sebelum meluncur membelah pulau-pulau besar hingga ke jantung Pulau Jawa.
Pengungkapan terbesar dalam sejarah narkotika Indonesia terjadi pada 21 Mei 2025. Tim gabungan dari BNN, Ditjen Bea Cukai, dan TNI AL menggagalkan penyelundupan sabu seberat hampir dua ton di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Kapal tanker bernama MT Sea Dragon Tarawa disergap dalam operasi dini hari. Di balik lambung kapal, tersembunyi kardus-kardus dalam kompartemen khusus berisi kemasan sabu produksi Cina—kemasan yang telah lama menjadi ciri khas sindikat internasional.
“Ini adalah pengungkapan terbesar sepanjang sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia,” tegas Kepala BNN RI Komjen Marthinus Hukom saat konferensi pers di Batam, 26 Mei lalu.
Skema penyelundupan sabu terorganisir dengan presisi. Barang dikirim dari Cina, masuk ke Malaysia, lalu diselundupkan lewat jalur laut ke pantai timur Sumatera: dari Kepulauan Riau, Tanjungbalai, Batubara, hingga Aceh Timur. Di titik-titik ini, sabu mulai diturunkan dan didistribusikan secara darat menuju Medan, Riau, Palembang, Lampung, dan akhirnya Pulau Jawa. Kota-kota besar di sepanjang jalur Trans-Sumatera menjadi simpul transit strategis.
Wilayah Aceh dan pesisir timur Sumatera kini menjadi tempat favorit para bandar. Selain geografisnya yang sulit dijangkau dan minim patroli laut, faktor sosial seperti pengangguran dan kemiskinan menjadi ladang subur rekrutmen kurir.
“Pola penyebaran ini sudah seperti nadi. Dari laut ke darat, seperti sistem peredaran darah. Sangat rapi,” ujar seorang perwira Bea Cukai yang tidak mau disebutkan namanya.
Nama Fredy Pratama kembali mencuat. Dari Thailand, ia mengendalikan jaringan raksasa lintas negara. Barang bukti sejak 2020 menunjukkan betapa luas jaringan ini: 10,2 ton sabu, 116 ribu ekstasi, dan lebih dari ratusan rekening bank untuk pencucian uang. Ia tidak sendiri. Sebanyak 39 tersangka telah ditangkap sejak Mei 2023.
Namun, Fredy bukanlah satu-satunya. Nama-nama seperti Muhammad Nasir, Freddy Budiman, dan Sucai menandai bab gelap sejarah narkotika Indonesia. Mereka adalah contoh nyata bagaimana peredaran sabu tidak berhenti meski pelaku utama berada dalam penjara.
Kisah Freddy Budiman adalah bukti nyata betapa sistem pemasyarakatan bisa dibajak. Ia mendirikan pabrik sabu di dalam Lapas Cipinang. Sementara Meirika Franola (Ola) bahkan sempat menerima grasi dari Presiden sebelum kembali ditangkap karena menyelundupkan sabu dari India.
Nama Zarima, si ratu ekstasi, mempertegas fenomena unik ini. Ia tertangkap membawa 30.000 butir ekstasi pada 1996, kabur ke Amerika, dideportasi, dan kembali tersangkut kasus serupa. Bahkan ia melahirkan anak saat masih dalam tahanan sebuah drama kemanusiaan di tengah tragedi narkotika.
Di Sumatera Selatan, bayang-bayang Widi Handoyo alias Sucai masih menghantui. Ia dikenal sebagai gembong asal Palembang yang tak hanya menyelundupkan ekstasi dalam jumlah besar, tetapi juga mengendalikan jaringan dari dalam Rutan. Kini, bekas anak buahnya, Lukman Wahyudi, kembali tertangkap membawa 20 kilogram sabu menandakan regenerasi jaringan berjalan tanpa henti.
Pemberantasan narkoba bukan sekadar operasi penangkapan. Ini perang ideologi dan ekonomi. Selama laut tetap terbuka dan darat tak steril, narkoba akan terus menyelinap seperti arus bawah. Para bandar besar memanfaatkan celah hukum, kelengahan aparat, dan realitas sosial masyarakat pesisir yang hidup pas-pasan.
“Selama ada permintaan, akan selalu ada pasokan,” ungkap seorang pejabat BNN di Palembang.
Pulau Sumatera bukan sekadar koridor transit narkoba. Ia telah menjadi medan tempur senyap dalam perang panjang melawan zat yang membunuh tanpa suara. Dan selama para dalang bisa memerintah dari balik jeruji, jalur-jalur sabu akan terus berdenyut, menyusup ke setiap pori bangsa.
Di tengah gegap gempita komitmen pemberantasan narkoba, fakta lapangan berbicara lain. Indonesia, dengan jutaan penduduk muda dan wilayah maritim yang luas, telah menjelma menjadi pasar emas bagi kartel narkotika internasional. Lebih dari sekadar korban, negeri ini mulai tampak seperti tuan rumah yang terlalu terbuka bagi masuknya barang haram dari luar negeri dan sayangnya, itu bukan tanpa sebab.
Jalur masuk sabu dari Cina yang menyusur Malaysia hingga pantai timur Sumatera adalah cerminan rapuhnya pengawasan maritim dan daratan kita. Tanpa kontrol yang ketat dan sistemik, Pulau Sumatera kini ibarat halaman depan rumah yang tak pernah dikunci terbuka, luas, dan penuh peluang bagi para bandar.
Meski aparat gencar melakukan penangkapan, yang tertangkap hanyalah ujung rantai. Yang lebih memprihatinkan adalah. Mengapa jalur itu terus digunakan dan tak kunjung ditutup?
Data pengungkapan menunjukkan tren yang mencemaskan. Dari 2020 hingga 2025, lebih dari 10 ton sabu, ratusan ribu butir ekstasi, dan uang triliunan rupiah berhasil disita. Tapi itu hanya serpihan kecil dari total peredaran yang nyata terjadi di lapangan. Jumlah itu membuktikan satu hal: Indonesia adalah pasar narkoba yang sangat prospektif.
Permintaan dalam negeri tinggi. Gaya hidup hedonis di kota besar, tekanan ekonomi di pinggiran, dan minimnya literasi bahaya narkoba menjadi kombinasi sempurna. Narkoba tak hanya jadi pelarian, tapi juga komoditas.
Fakta menyedihkan lainnya: para pelaku tidak hanya berasal dari luar. Banyak dari mereka adalah anak negeri sendiri. Bahkan, beberapa tokoh jaringan narkoba terbesar justru mengendalikan operasi dari dalam penjara di Indonesia.
Otokritik bukan tudingan kosong. Pemerintah harus jujur bahwa terlalu lama menempatkan perang narkoba hanya di sisi penindakan. Sementara pencegahan, rehabilitasi, dan pengetatan jalur masuk masih tertinggal jauh. Bahkan, kebocoran informasi, aparat yang bermain dua kaki, hingga minimnya koordinasi antar lembaga, menjadi celah bagi bandar untuk masuk lebih dalam.
Ketika satu kapal disergap, ada tiga kapal lain yang lolos. Ketika satu bandar dihukum mati, ada sepuluh lainnya yang lahir dari sistem yang rusak. Sumatera adalah pintu utama karena kelemahan kita sendiri. Pelabuhan-pelabuhan kecil tak dijaga. Sistem pelacakan tidak terintegrasi. Nelayan lokal mudah disuap. Dan pantai-pantai panjang kita hanya dijaga oleh moral.
Uang Lebih tegas dari kekuasaan, Bandar internasional melihat Indonesia bukan sekadar target pasar, tapi surga logistik. Dengan uang, mereka bisa menyuap, menyusup, bahkan menguasai. Ketika sabu bisa diselundupkan dalam kapal tanker dan dikubur dalam kontainer pendingin, pertanyaannya adalah siapa yang memungkinkan itu?
Kita harus berani bertanya: apakah negara ini benar-benar serius melawan narkoba? Atau hanya bermain citra di media saat tangkapan besar terjadi, lalu kembali diam saat kartel mulai membangun jalurnya lagi?
Tak ada jalan keluar dari krisis narkoba tanpa keberanian untuk bercermin. Indonesia bukan semata korban, tetapi juga bagian dari masalah. Terlalu lama kita membiarkan pantai-pantai kita dijaga oleh niat baik semata. Terlalu lama pula kita meninabobokan publik dengan slogan “perang narkoba” tanpa disertai reformasi.
Jika pemerintah tidak segera menutup pintu-pintu masuk di Sumatera dan wilayah perbatasan lainnya, Indonesia bukan lagi ladang subur narkoba tetapi akan menjadi pabriknya. Dan ketika itu terjadi, semua bentuk penyesalan sudah tak akan berguna.(SM)