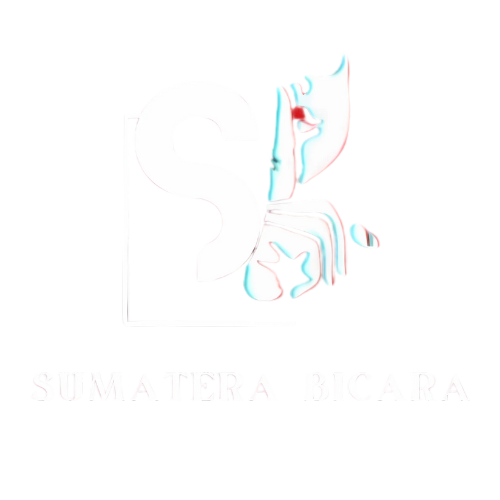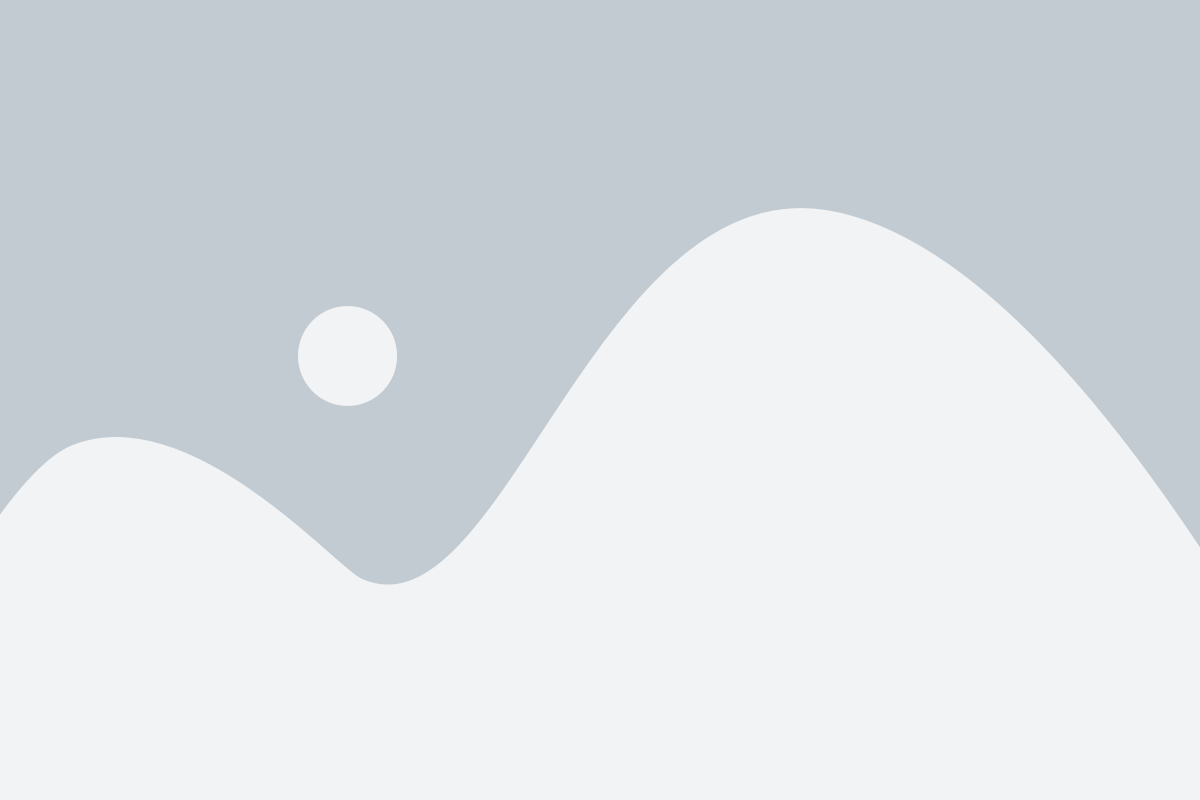//Sengketa 4 Pulau dan Bara Dingin di Jantung Istana
Jakarta—Drama politik Indonesia kembali bergelora, kali ini dari garis perbatasan laut antara Aceh dan Sumatera Utara. Di balik sengketa empat pulau kecil, terselip benturan besar antara dua figur besar negeri ini, Mualem Muzakir Manaf, sang jenderal gerilya yang bangkit dari hutan belantara Aceh, dan Prof. Tito Karnavian, jenderal intelektual yang berakar dari elite meja birokrasi pusat.
Dua pemimpin ini berdiri di kutub yang sama-sama kuat satu menyuarakan kedaulatan sejarah dan identitas Aceh, satu lagi menjunjung kodifikasi wilayah dan ketertiban administrasi nasional.
Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan: keempat pulau yang sempat diklaim Sumut dalam Kepmendagri 300.2.2-2138/2025, kini resmi dinyatakan sebagai bagian dari Aceh, berdasarkan dokumen administratif dan historis yang dinilai sah.
Namun, keputusan itu tak lahir tanpa gesekan. Di balik meja-meja rapat Setneg, terjadi pertarungan narasi dan legitimasi antara dua karakter yang sangat kontras.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf bukanlah sekadar pejabat. Ia simbol perjuangan Aceh. Dari gurun Libya hingga rimba-rimba Sumatra, Mualem menghabiskan separuh hidupnya dalam barisan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ia menatap pulau-pulau itu bukan hanya sebagai titik koordinat, tetapi sebagai simbol martabat Aceh.
“Saya bukan Gubernur yang lahir dari ruang AC,” ujar Mualem dalam sebuah wawancara terbatas. “Empat pulau ini bukan soal kode wilayah, ini soal hak Aceh.” ujarnya
Mualem menggiring massa rakyat dan elite Aceh berdiri di belakangnya, menolak Kepmendagri yang awalnya memasukkan empat pulau ke wilayah Sumut. Di atas kertas, ia menulis surat protes. Di bawah tanah, dukungan moral dari tokoh adat, pejuang GAM lama, dan aktivis sipil terus berdatangan.
Di sisi lain meja, berdiri Tito Karnavian, Mendagri sekaligus mantan Kapolri dan arsitek Densus 88. Ia dikenal dengan kecerdasan akademik, disiplin strategi, dan ketegasan hukum. Tito memandang negara sebagai entitas tertib, bukan kumpulan emosi sejarah.
Keputusan awalnya yang mengklasifikasi pulau-pulau itu masuk Sumut berbasis kode wilayah, justru jadi bumerang. Reaksi keras dari Aceh membuat posisinya terguncang. Namun Tito tetap diplomatis.
Tito tetap dingin, tak mengumbar pernyataan. Namun, tim dari Kemendagri dan BPN diketahui mengirim pakar untuk menyusun ‘peta kebenaran’ yang bisa dipertanggungjawabkan di meja hukum dan sejarah.
Melihat bara makin memerah, Presiden Prabowo mengambil sikap. Dalam rapat tertutup, memanggil semua pihak termasuk Gubernur Sumut Bobby Nasution dan perwakilan DPR untuk menyelesaikan konflik ini dengan kepala dingin. “Empat pulau itu milik Aceh,” ujarnya tegas Prabowo, mengakhiri spekulasi.
Namun, keputusan ini juga menjadi semacam penegasan: Jakarta harus mendengar suara pinggiran, bukan hanya memegang data peta dari balik layar monitor.
Perseteruan ini bukan soal siapa memiliki tanah, tetapi tentang siapa yang memiliki narasi. Dalam satu sisi, Muzakir membawa semangat rakyat. Di sisi lain, Tito membawa kepastian administrasi. Perseteruan keduanya mencerminkan wajah Indonesia hari ini antara politik dari bawah dan birokrasi dari atas.
Indonesia akhirnya tak hanya belajar tentang empat pulau, tapi juga tentang dua jenderal satu dari hutan, satu dari meja. Dan bagaimana negeri ini harus belajar menyeimbangkan keduanya.(SM)